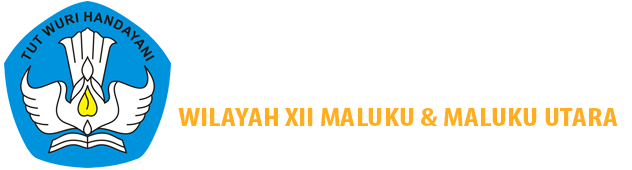PENDIDIKAN DOKTOR “BASA-BASI”

28 February 2017
by Supriadi Rustad
Mulai dari tulisan ini saya memutuskan untuk menggunakan istilah “basa-basi” guna memperhalus ungkapan yang sebelumnya saya gunakan untuk menyebut mutu rendah. Saya belajar, dan akhirnya menyadari bahwa masyarakat Indonesia ternyata lebih menyukai penghalusan bahasa yang tetap memuat selera humor (joke) daripada yang lugas meski maknanya sama. Melalui tulisan ini pula saya meralat ungkapan abal-abal yang sebelumnya sempat saya gunakan dan menggantinya dengan “basa-basi”.
Mencermati rangking Webometrics perguruan tinggi di Indonesia edisi Januari 2017 dan sebelumnya, ada data menarik. Secara umum rangking dunia perguruan tinggi di Indonesia mengalami penurunan signifikan, meski rangking nasional naik. Sebagai contoh Universitas Dian Nuswantoro Semarang yang hingga saat ini belum menyelenggarakan pendidikan doktor. Rangking nasional universitas di tengah kota Semarang ini menyodok ke peringkat ke-24 dari semester sebelumnya pada peringkat ke-31. Namun ternyata rangking dunianya turun, dari peringkat ke-3356 ke peringkat ke-3468. Hal demikian ini secara umum terjadi pada perguruan tinggi lainnya, dan ini menunjukkan bahwa di kancah global, daya saing perguruan tinggi Indonesia melemah. Ya, kita sepertinya lebih sibuk “bertarung” di dalam negeri.
Selain daya saing yang melemah, terdapat satu data yang menggelitik pikiran. Data tersebut ada di kolom keempat indikator perangkingan, yang diberi judul Excelence. Tak habis pikir, kenapa pada aspek ini sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia memiliki peringkat yang sama, yaitu ke-5778. Apakah Webometrics tumpul dan tidak memiliki determinasi ketika berhadapan dengan indikator ini? Ya, lembaga perangkingan ini tampak tidak memiliki resolusi lagi untuk aspek ini.
Saya coba tengok tiga kolom lainnya. Ternyata normal dan konsisten. Baik indikator Presence, Visibility, maupun Openess, ketiganya konsisten menunjukkan rangking bahkan hingga peringkat puluhan ribu. Ya, ketidaknormalan hanya terjadi di indikator keempat, Excelence. Apa sesungguhnya yang terjadi?
Saya akhirnya memahami bahwa Webometrics ternyata bukan hanya melakukan perangkingan terhadap web atau laman, tetapi juga kinerja akademik perguruan tinggi yang sangat mendasar. Sistem perangkingan ini mengompilasi data karya ilmiah insan perguruan tinggi yang reliabel dan sahih dari berbagai sumber data terbuka (open data sources). Sebenarnya tentang hal ini telah dijelaskan dengan baik oleh lembaga perangkingan yang dikelola oleh Badan Penelitian Nasional Spanyol itu melalui laman resmi pada menu FAQs.
Indikator Excelence merujuk kepada jumlah artikel karya sivitas akademika perguruan tinggi yang dipublikasikan. Tidak tanggung-tanggung, Webometrics mengambil data ini dari artikel yang terindeks di Scimago Institutions Rangking (SIR) pada kurun 2010-2014. Pada perhitungan rangking edisi Januari 2017, indikator ini memiliki bobot yang lumayan besar, yaitu 30 %.
Pada indikator ini, angka 5778 merupakan angka keramat, karena peringkat ini diduduki oleh hampir sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia. Tercatat hanya 29 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki peringkat selain itu. Hingga saat ini saya belum bisa menemukan peringkat di bawahnya, misalnya peringkat ke-5779, ke-5790, dan seterusnya. Dalam konteks ini, peringkat ke-5778 merupakan peringkat terminal, tidak ada lanjutannya.
Untuk semesta himpunan bilangan positif, angka 0 (nol) lebih cocok menjelaskan fenomena peringkat ke-5778 ini. Dari 4.500-an perguruan tinggi di Indonesia, hanya 29 perguruan tinggi yang memiliki nilai selain nol, sedangkan perguruan tinggi lainnya memiliki nilai nol. Sungguh sangat mengherankan, karena sejumlah perguruan tinggi yang memiliki peringkat Excelence 5778 (nilai nol) itu adalah mereka yang mendapatkan peringkat akreditasi institusi A. Lebih dari separuh perguruan tinggi terakreditasi institusi A dinilai lemah daya saingnya oleh Webometrics!
Instrumen akreditasi disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Mengingat standar nasional merupakan standar minimal, maka instrumen akreditasi semestinya tidak hanya mengukur standar, tetapi juga bisa mengukur dampak dari keberadaan standar itu sebagai perwujudan dari daya saing perguruan tinggi. Untuk peringkat akreditasi baik (C) atau sangat baik (B), intrumen yang sekarang ada nampaknya sudah mencukupi. Namun untuk meraih peringkat akreditasi unggul (A), tampaknya harus dibuat parameter distinctive yang bisa mencerminkan sisi keunggulan (daya saing) perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan keterbukaan BAN PT, saya optimistis instrumen akreditasi dapat disempurnakan supaya akreditasi lebih objektif menjawab pertayaan “apa” kontribusi perguruan tinggi daripada menjawab pertanyaan “siapa”.
Publikasi Doktor, ke Mana?
Yang sangat mengganggu pikiran adalah bahwa sejumlah perguruan tinggi yang daya saingnya lemah, termasuk mereka yang menyelenggarakan pendidikan doktor yang sudah dikenal cukup lama. Ke manakah publikasi karya ilmiah para doktor itu sehingga tidak terindeks di SIR? Ah… jangankan di SIR atau Google Scholar, di repositori perguruan tinggi saja karya ilmiah tersebut belum tentu bisa ditemukan.
Dosen dengan jabatan guru besar dan lektor kepala dituntut menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan baik nasional maupun internasional. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 memuat hal-hal yang mengatur pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor dikaitkan dengan kewajiban publikasi karya ilmiah dosen. Baru-baru ini Menristekdikti menyatakan setidaknya 1200 guru besar tidak melakukan publikasi. Menarik untuk diteliti hubungan antara profesor yang tidak melakukan publikasi dengan latar belakang pendidikan doktornya. Adakah kesimpulan yang mengarah kepada akar persoalan pendidikan doktor basa-basi?.
Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), doktor memiliki derajat kualifikasi 9 dengan 3 (tiga) deskripsi sebagai berikut. Pertama, doktor mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Jelas bahwa kompetensi doktor itu kompetensi riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan mengembangkan proyek atau program.
Kedua, doktor mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Pergulatan seorang doktor adalah menemukan solusi keilmuwan atas peroalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Ketiga, doktor mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermafaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Pengakuan terhadap seorang doktor sebagai academic leader antara lain dapat melalui karya ilmiah yang dihasilkan. Kiranya tak berlebihan sebutan doktor basa-basi untuk mereka yang takut karya ilmiahnya dibaca orang lain.
Pendidikan doktor merupakan jenjang pendidikan yang menjadi tumpuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui suatu kelompok penelitian (research group) yang dipimpin seorang profesor, jenjang ini mestinya menjadi pelopor pembangunan suasana penelitian di kampus, karena memiliki tugas untuk mengembangkan ilmu bersama adik-adiknya mahasiswa S2 dan S1. Kelompok penelitian demikian ini diharapkan menjadi “mesin” publikasi artikel hasil penelitian sehingga bisa terdaftar di lembaga perangkingan baik nasional maupun internasional. Jika suatu pendidikan doktor tidak mampu berkontribusi pada jumlah artikel yang berkualitas, maka “mesin” publikasi perguruan tinggi yang bersangkutan dapat dikatakan telah berada pada “sakaratul maut”.
Pendidikan doktor basa-basi merujuk kepada pendidikan doktor yang tidak mampu menghasilkan artikel hasil penelitian yang berkualitas atau produk lain yang setara. Ciri-ciri pendidikan doktor jenis ini antara lain ia tidak memiliki interaksi keilmuwan dengan jenjang pendidikan sarjana dan magister, bahkan di antara mahasiswa dari jenjang S1, S2, dan S3 pada prodi/bidang yang sama tidak saling mengenal. Pembelajaran dilakukan secara klasikal dan terpisah dari kegiatan akademik lainnya dengan label kelas tertentu.
Ciri berikutnya adalah tidak memiliki kelompok dan juga proyek penelitian sebagai isu bersama yang hendak dicarikan solusinya. Tema disertasi tidak saling berhubungan satu sama lain, termasuk juga tidak ada kaitannya dengan skripsi dan tesis pada jenjang sebelumnya. Perdebatan dan wacana yang berkembang di seputar tema disertasi, baik oleh promotor, promovendus, maupun khalayak di komunitas ini dapat dikatagorikan sebagai isu basi dari sebuah basa-basi yang sejatinya tidak perlu ada. Nyaris tidak dijumpai “saling kutip” pada karya lulusannya.
Mutu pendidikan doktor antara lain dapat dinilai melalui disertasi yang dihasilkan. Pada pendidikan doktor basa-basi, tema disertasi umumnya jauh dari substansi yang terkait dengan evaluasi (review) terhadap suatu ilmu pengetahuan, tetapi didominasi oleh tema yang terkait dengan evaluasi program dan evaluasi proyek. Mencermati sejumlah disertasi di sejumlah program pascasarjana, saya mengamati telaah dan analisis sejumlah disertasi lebih rendah dari hal yang sama pada skripsi sarjana atau bahkan D3.
Ciri paling aneh dari pendidikan doktor basa-basi adalah lulusnya lebih cepat dari pendidikan doktor “beneran”. Umumnya para doktor ini lulus dalam waktu sekira 2 tahun, suatu selang waktu yang di perguruan tinggi di Amerika hanya khusus untuk menempuh mata kuliah inti sebelum kandidasi. Saya sendiri menghabiskan waktu 7 tahun di ITB sebelum dinyatakan lulus doktor Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2003. Ah, jadi ingat hampir tiap malam tidur di laboratorium elektomagnetik Fisika Bumi beralaskan seadanya.
Perangkingan webometrics dapat dimanfaatkan oleh Kemenristekdikti untuk memperbaiki pola manajemen perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan perangkingan tersebut, hanya ada 29 perguruan tinggi yang memiliki tanda-tanda bisa tumbuh menjadi universitas riset (research university), sementara perguruan tinggi lainnya lebih cocok diarahkan menjadi universitas pengajaran (teaching university). Jika kita memiliki kebijakan yang jelas tentang pengembagan perguruan tinggi ke depan, maka berbagai macam kebijakan turunannya dapat diarahkan lebih efektif dan efisien, termasuk kebijakan penelitian dan kebijakan pascasarjana.
Bisa jadi pemilahan universitas riset dan universitas pengajaran kurang sejalan dengan konsep tridharma perguruan tinggi. Konsep ini menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tugas di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara komprehensif. Jika kita memiliki universitas pengajaran, maka guru besarnya adalah guru besar pengajaran, dan doktornya juga doktor pengajaran. Aneh rasanya. karena spesifikasi utama doktor itu adalah kompetensinya di bidang riset sesuai dengan KKNI.
Dibandingkan dengan jenjang S1 dan S2, jenjang pendidikan doktor di Indonesia merupakan program yang paling tidak terkendali mutunya. Sejumlah perguruan tinggi telah mengumumkan kriteria kelulusan, namun banyak juga yang tidak memiliki kriteria kelulusan yang berkaitan dengan kualitas. Semestinya Kemenristekdikti segera melakukan penertiban kepada program pascasarjana yang hingga saat ini tidak mencantumkan kriteria kelulusan sesuai Permenristekdikti No. 44 tentang SN Dikti.
—Supriadi Rustad, Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi.
Sumber : http://supriadirustad.blog.dinus.ac.id/2017/02/28/pendidikan-doktor-basa-basi/
Baca juga : “Udang Besar” di Balik Ijazah Abal-abal